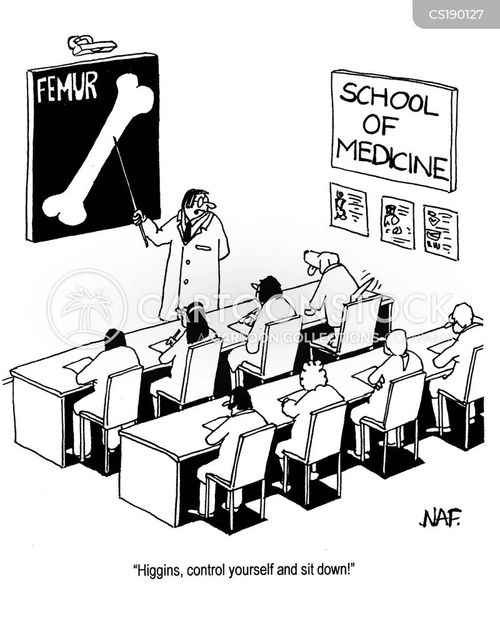Di sekitar akhir tahun 2010, saya pernah menculik istri saya dari tempat PTT-nya di pulau Peling, Sulawesi Tengah ke Makassar. Tujuannya satu, membujuk dia untuk mau sekolah lagi. Saat itu dia sudah dua tahun PTT di pulau itu. Setelah melalui bujuk rayu, tepatnya mungkin "indoktrinasi", akhirnya dia pun bersedia. Saya pun bersibuk-sibuk mengantarnya kesana kemari, mengurus berkas, meminta surat rekomendasi, mendaftar dan ujian. Alhamdulillah dia diterima di Neurologi FK UNHAS.
Mengapa saya bersikeras memintanya bersekolah lagi? Tentu saja karena suatu ketika dia harus menemani saya di Makassar. Ada alasan untuk dia tidak jauh. Saya pun khawatir jika dia terlalu lama di tempat PTT-nya keinginannya untuk bersekolah bisa pudar. Dan spesialis, pikiran sederhana saya saat itu adalah agar dia lebih kompetitif di masa depan. Toh jumlah spesialis belum banyak dibandingkan kebutuhan Indonesia secara keseluruhan. Dibandingkan dengan dokter umum yang jumlahnya 80 ribuan lebih, dokter spesialis cuma berjumlah sekitar 12 ribuan lebih dari data Dikti 2014.
Istri saya mungkin sedikit beruntung bisa mengikuti dan melalui proses pendidikan ini. Jika kita mau jujur, coba acung tangan teman-teman dokter umum yang tidak punya niat melanjutkan pendidikan spesialisasi atau teman-teman yang ingin selamanya di klinik atau puskesmas. Mungkin banyak yang seperti itu, tapi tak bisa dipungkiri bahwa banyak juga yang berniat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang spesialisasi. Pertanyaannya mengapa?
Selain alasan ideal untuk menambah pengetahuan dan keterampilan klinis, tak bisa dipungkiri tingkat kesejahteraan dokter spesialis jauh lebih tinggi dari dokter umum adalah juga faktor utama. Dari sebuah survei yang dilaporkan di sebuah media disebutkan kadang angka gajinya sangat jauh sekali berbeda.
Dan kita tidak bisa memprotesnya, toh itu adalah "reward" atas keahlian mereka, keahlian yang diperoleh dengan tidak mudah tapi dengan perjuangan yang menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Saat yang lain tidak berpayah-payah belajar atau mungkin tidak beruntung mendapatkan kesempatan itu, ada sekelompok dokter lain yang menghabiskan hampir sekitar 5 tahun dari umurnya untuk mendalami lagi ilmu kedokteran.
Selain ilmu, kesejahteraan, hal lain yang tak kalah menariknya dari para spesialis adalah prestise yang mereka dapatkan dari masyarakat. Psikologi masyarakat kita masih selalu condong saat sakit sedikit ya berobat ke dokter spesialis walaupun mungkin penyakit tersebut boleh jadi bisa diobati oleh dokter umum. Di sebuah tempat yang pernah saya kunjungi di salah satu pulau di timur Indonesia, sebuah klinik langsung sepi karena spesialisnya ramai-ramai pindah ke klinik yang lain walau disana tetap ada dokter umum.
Nah soal ini seperti jugalah yang membuat kadang layanan primer kita tidak berkesinambungan. Sebuah contoh sederhana saat kami sekitar dua tahun lalu melakukan survey terhadap buku panduan praktik klinis di layanan primer di sebuah kabupaten di Jawa Barat, informasinya jadi kurang akurat. Cuma selang beberapa bulan, dokter klinik tersebut diganti karena melanjutkan sekolah. Penggantinya "fresh graduate" yang entah berapa lama akan bertahan disana dan baru mau mulai belajar lagi. Saya kira fenomena serupa ini jamak terjadi dimana-mana.
Sayangnya tak semua dokter umum punya kesempatan melanjutkan ke jenjang spesialisasi. Ada beberapa alasan yang bisa disebut, pertama biaya pendidikan spesialis yang mahal. Untungnya kemarin ada beasiswa dari pemerintah dan ada juga pemda yang memberikan beasiswa bagi dokter di daerahnya. Kedua, seleksi pendidikan spesialisasi yang sangat ketat dan kapasitas FK untuk menerima mahasiswa sangat terbatas membuat jumlah yang diterima sangat sedikit. Banyak dokter yang berulang-ulang test namun tidak lulus-lulus juga.
Terlepas dari pro kontra soal DLP sebenarnya ada bagian menarik dari konsep ini bagi dokter umum terutama soal peningkatan status dan kesejahteraannya. Bagi mereka yang tidak tertarik atau mungkin tidak beruntung masuk spesialisasi, bekerja di layanan primer bisa jadi pilihan menarik di masa depan, bukan seledar persinggahan. Apalagi jika gajinya dijamin tidak sekecil yang diterima dokter umum sekarang karena status dan kompetensi mereka terangkat.
Kita memang harus mengakui bahwa tantangan soal DLP ini tak mudah. Saat ini organisasi profesi menolak. Jika pun pemerintah bersikeras tetap menjalankan tentu tidak mudah nanti bagi lulusannya. Belum lagi soal kesiapan fakultas kedokteran untuk menjalankan program studi baru ini. Meski saya dengar-dengar sudah ada FK negeri yang siap menjadi semacam laboratorium awal.
Permasalahan terbesarnya memang pada soal "teknis" bagaimana mengadakan DLP ini, kalau melihat konsepnya sih menarik untuk dokter umun. Menyekolahkan 80 ribu dokter umum menjadi DLP tidaklah mudah. Walaupun dikatakan ada fase transisi tetap butuh waktu lama. Apalagi jumlah FK yang dianggap layak menjalankannya tidak banyak.
Terlepas dari segala kebisingan perdebatannya, mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa ada substansi penting yang jangan sampai terlupakan yakni soal peningkatan kompetensi dan juga kesejahteraan dokter umum. Apakah nanti dengan DLP atau tanpa DLP. DLP dengan sekolah lagi dua tahun atau dengan cara lain. Ah semoga ada jalan keluar dan titik temu dari kerumitan ini. Hehehe
(Kanazawa, 81215)